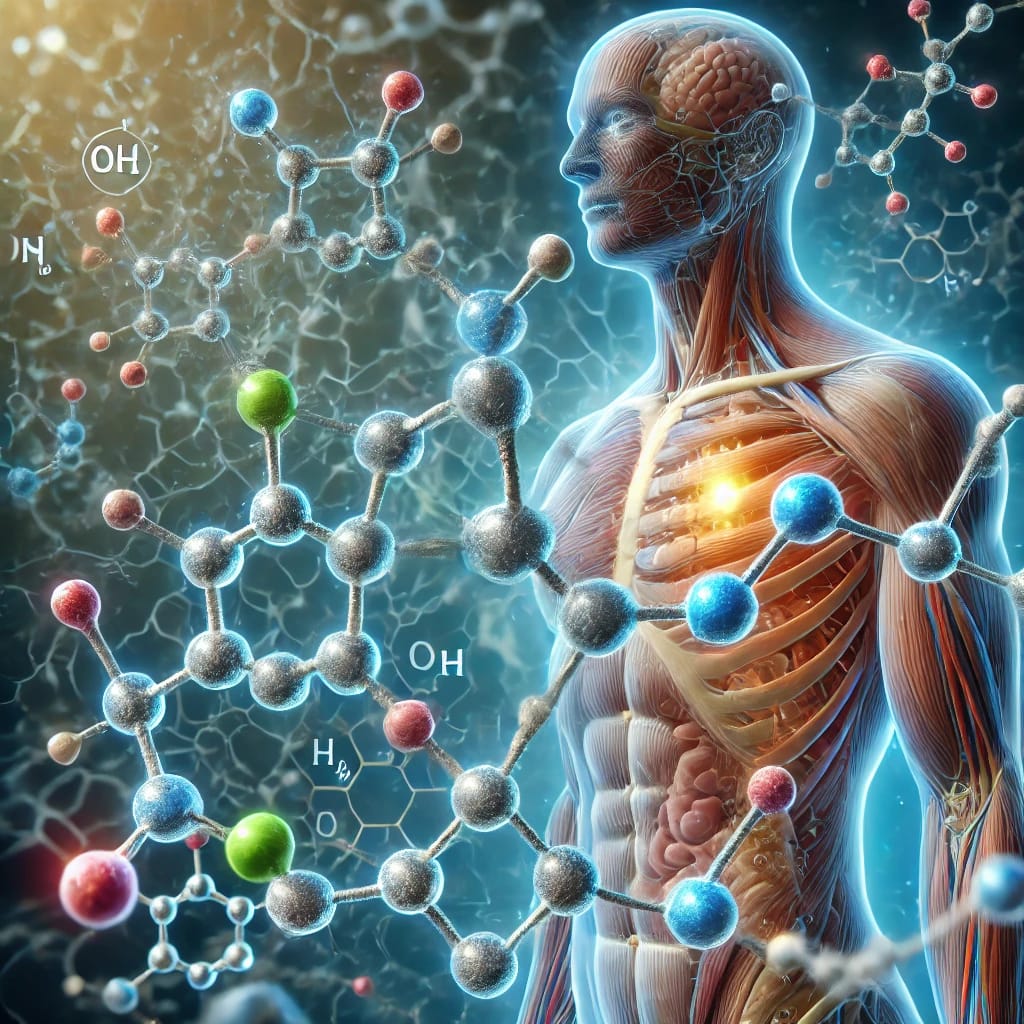Makna syukur sebagai mata air—sumber ketenangan yang tak pernah kering, yang terus mengalir meski dalam kesulitan, yang membuat jiwa tetap hidup dan tumbuh meski dalam keterbatasan. Sebagaimana mata air memberi kehidupan pada lingkungan sekitarnya, syukur yang mengalir dari hati memberi kehidupan pada jiwa dan kebaikan pada lingkungan sosial.
Oleh: Arda Dinata
“Dalam hembusan nafas yang kita hirup, tersimpan sejuta rahasia kemurahan semesta. Setiap detak jantung adalah puisi syukur yang jarang kita baca dengan saksama.”
Pagi itu, di lereng Gunung Gede, seorang petani tua bernama Mbah Karto sedang berjalan menyusuri kebun tehnya yang menguning. Tiga bulan tanpa hujan telah membuatnya merugi. Tanaman yang biasanya rimbun kini layu, daun-daun mengering, dan pucuk-pucuk muda—yang bernilai jual tinggi—tidak lagi tumbuh. Ketika ditanya oleh cucunya mengapa ia tidak mengeluh, Mbah Karto justru tersenyum.
“Nak,” ujarnya sambil menunjuk ke arah mata air kecil yang mengalir di sudut kebunnya. “Lihat mata air itu. Ketika musim hujan, arusnya deras, semua orang mengabaikannya. Tapi di kemarau panjang seperti ini, mata air kecil itulah yang membuat kita bertahan. Ia terus mengalir meski tipis, memberi minum untuk kebun dan keluarga kita. Alhamdulillah, kita masih punya mata air.”
Ia melanjutkan, “Begitulah syukur. Ia seperti mata air dalam kehidupan. Ketika kesulitan datang, syukur yang akan membuat kita tetap bertahan, melihat yang masih ada, bukan yang telah hilang. Al-ḥamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn—segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dulu kakekku mengajariku untuk mengucapkannya setiap kali melihat mata air, karena air adalah rahmat-Nya yang paling nyata.”
Kisah sederhana Mbah Karto membawa kita pada refleksi tentang hakikat syukur dalam kehidupan. Alhamdulillah, sebuah ungkapan yang sering meluncur dari mulut namun jarang sungguh-sungguh mengalir dari hati. Ia telah menjadi respons otomatis terhadap kabar baik atau ucapan konvensional dalam akhir doa. Namun benarkah kita telah memahami dan menghayati makna terdalam dari ungkapan ini?
Al-ḥamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn adalah ayat pembuka dalam Surah Al-Fatihah yang dianggap sebagai intisari Al-Qur’an. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya “Ihya Ulumuddin”, syukur memiliki tiga dimensi: syukur dengan hati (ma’rifah), syukur dengan lisan (tsana’), dan syukur dengan anggota badan (ta’ah). Dengan kata lain, syukur sejati melibatkan pengenalan akan nikmat dalam hati, pengucapan dengan lisan, dan perwujudan dalam tindakan (Al-Ghazali, 2011).
Filsuf Muslim kontemporer, Seyyed Hossein Nasr, dalam bukunya “Knowledge and the Sacred” (1989), menjelaskan bahwa hamdalah (pengucapan alhamdulillah) bukan sekadar ungkapan terima kasih, tetapi pengakuan bahwa segala kebaikan, keindahan, dan kesempurnaan pada hakikatnya berasal dari Allah dan milik-Nya. Dengan mengucapkan alhamdulillah, seorang muslim tidak hanya berterima kasih atas nikmat tertentu, tetapi juga mengakui bahwa Allah adalah sumber segala puji dan kebaikan itu sendiri.
Menariknya, studi psikologi kontemporer telah menemukan korelasi positif antara rasa syukur dan kesejahteraan psikologis. Penelitian Robert Emmons dan Michael McCullough (2003) menunjukkan bahwa praktik bersyukur secara teratur dapat meningkatkan mood positif, mengurangi depresi, meningkatkan energi, dan bahkan memperbaiki kualitas tidur. Studi lain oleh Martin Seligman, pelopor psikologi positif, menemukan bahwa menulis surat terima kasih kepada seseorang yang belum pernah diberi ungkapan terima kasih secara layak dapat meningkatkan kebahagiaan dan menurunkan gejala depresi hingga satu bulan (Seligman et al., 2005).
Di tengah masyarakat modern yang semakin materialistis dan konsumeristis, syukur seakan menjadi kebajikan yang langka. Kita hidup dalam budaya yang terus menerus menciptakan rasa “kurang” dan “belum cukup”. Iklan-iklan membombardir kita dengan pesan bahwa kebahagiaan terletak pada produk terbaru, rumah lebih besar, mobil lebih mewah, atau pakaian lebih bergaya. Media sosial memperparah situasi ini dengan menciptakan budaya perbandingan yang tak berujung. Kita melihat “highlights reel” kehidupan orang lain, dan mulai mempertanyakan kecukupan dalam hidup kita sendiri.
Filosof Jerman, Friedrich Nietzsche, meski dikenal sebagai kritikus agama, mengakui pentingnya syukur. Ia menulis, “Yang terbaik dalam kebahagiaan kita adalah ia membuat kita lebih mampu untuk berbuat baik.” Nietzsche melihat bahwa kondisi bahagia, yang sering muncul dari rasa syukur, bukanlah tujuan akhir melainkan kondisi yang memampukan kita untuk memberi dan berbuat lebih banyak kebaikan (Nietzsche, 1974/1887).
Namun, perlu diakui bahwa bersyukur di tengah kesulitan adalah tantangan tersendiri. Bagaimana kita bisa mengucapkan alhamdulillah ketika kehilangan pekerjaan, menghadapi penyakit serius, atau ditinggalkan orang tercinta? Di sinilah letak kedalaman spiritual dari konsep hamdalah. Bersyukur bukan berarti mengabaikan kesulitan atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Bersyukur adalah kemampuan untuk tetap melihat kebaikan yang masih ada, seperti mata air Mbah Karto yang terus mengalir meski tipis di musim kemarau.
Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam “Madarijus Salikin” menjelaskan bahwa tingkatan tertinggi dari syukur adalah syukur atas kesulitan dan cobaan. Hal ini karena seorang hamba menyadari bahwa di balik setiap ujian terdapat hikmah dan kebaikan yang mungkin belum ia pahami (Ibnu Qayyim, 2009). Pemahaman ini sejalan dengan ayat Al-Qur’an: “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 216).